Sejak kemunculannya pertama kali pada kisaran Desember 2019, virus Corona yang juga dikenal dengan Covid-19 ini berhasil menarik perhatian dunia. Penyebarannya yang cukup cepat disertai dengan jumlah pasien yang positif mengidap virus ini semakin bertambah membuatnya menjadi salah satu pandemi yang membuat mayoritas penduduk bumi ini berada dalam ketakutan dan kekhawatiran. Hingga Jumat, 17 April 2020, virus yang awalnya berkembang di Wuhan, Cina ini telah menjangkiti sekitar 2.173.432 jiwa di seluruh dunia dan 5.923 jiwa di Indonesia. Jumlah ini diperkirakan akan terus mengalami tren kenaikan karena jumlah orang dalam pengawasan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) dalam lingkup Indonesia masih berkisar sekitar 173.732 jiwa dan 12.610 jiwa.
Tak ayal, virus ini dianggap menjadi sebuah fenomena besar dalam sejarah umat manusia di era modern ini. Berbagai ketakutan dan kekhawatiran bercampur baur dengan kegigihan dan harapan di tengah masyarakat. Respon masyarakat yang beragam lahir dari sudut pandang mereka yang beragam pula. Tak terkecuali, tentang posisi pandemi ini, apakah ia suatu ‘ujian’, atau ‘cobaan’, atau bahkan ‘azab’ bagi penduduk Bumi ini?
Seberapa pun modern umat manusia, mereka tidak dapat dipisahkan dari kenyataan bahwa mereka meyakini adanya ‘kehendak’ di luar kehendak mereka. Bencana alam, wabah penyakit, kematian, dan berbagai bencana kemanusiaan dalam aspek sekecil-kecilnya merupakan beberapa hal yang seringkali ‘meleset’ dari prediksi manusia. Dalam ranah teologis, hal-hal tersebut seringkali disebut dengan takdir. Baik takdir baik maupun takdir buruk, semuanya merupakan rahasia dari Tuhan, pemilik kekuatan di atas kekuatan manusia.
Dalam kacamata teologis Islam, berbagai hal yang terjadi pada manusia dan dunia sekitarnya merupakan sebuah takdir yang telah ditetapkan. Kadangkala ia merupakan ‘ujian’ dariNya, ‘cobaan’, atau bahkan ‘azab’ atau hukuman yang diturunkan kepada umat manusia. Berbagai rentetan kisah sejarah membuktikan ‘kekuatan’ sebuah takdir, mulai dari banjir di zaman Nabi Nuh, musim paceklik hebat di zaman Nabi Ya’qub dan Nabi Yusuf, gempa bumi dahsyat yang diiringi angin kencang dan hujan batu di zaman Nabi Luth, hingga berbagai wabah yang diturunkan di Mesir pada zaman Nabi Musa adalah buktinya.
Tak terkecuali pandemi Covid-19 ini. Sejak awal kemunculannya di provinsi Wuhan, Cina, ia sudah dikait-kaitkan dengan tingkah laku penduduk daerah tersebut. Mereka dianggap ‘layak’ mengidap berbagai penyakit yang disebabkan virus ini karena mereka telah melakukan berbagai kejahatan dan kedhaliman. Mulai dari ideologi yang mereka anut, makanan yang mereka konsumsi, hingga perbuatan mereka kepada salah satu etnis penghuni negara tersebut. Seluruh hal tersebut menjadi legitimasi turunnya ‘azab’ berupa virus tersebut kepada mereka.
Ketika virus ini masih berada di Cina, tuduhan tersebut terasa sangat beralasan. Alih-alih prihatin dan memberikan pertolongan kepada negara tersebut, justru lebih banyak mereka yang ‘mengucapkan syukur’ atas turunnya azab tersebut. Bahkan, ketika mulai menyebar ke beberapa negara, banyak pihak yang mengklaim bahwa virus ini hanya menjangkiti penduduk etnis tertentu. Artinya, mereka di luar etnis tersebut tetap aman sentosa dan terhindar dari paparan virus tersebut.
Tuduhan tersebut belum reda, kita telah dikejutkan dengan fakta bahwa virus tersebut telah memasuki negeri kita tercinta. Pasien yang terindikasi positif mengidap virus tersebut juga tidak lolos dari berbagai tuduhan telah membawa penyakit tersebut ke Indonesia dan menularkannya kepada banyak orang. Namun, hal tersebut sudah terlambat. Hari ini, sudah ada lebih dari 5.923 jiwa di Indonesia yang positif terjangkiti virus tersebut, 520 di antaranya bahkan telah meninggal dunia.
Fenomena berbeda dapat kita saksikan ketika virus tersebut menjangkiti orang-orang yang menurut kita adalah seorang yang taat beragama dan berkepribadian santun. Kita akan mengatakan (bahkan meyakini) bahwa virus tersebut merupakan sebuah ‘ujian’ bagi seorang yang beriman untuk meningkatkan kadar keimanan dan derajatnya di hadapan Allah SWT. Bukannya sebuah ‘azab’ seperti pasien lainnya.
Di sini kita bisa melihat sebuah hal yang cukup ironis. Virus yang sama, terjangkiti dengan indikasi atau gejala yang kurang lebih sama, namun memiliki pemaknaan yang berbeda. Bila yang satu merupakan ‘azab’ dan mengharuskan seseorang untuk segera bertaubat, adapun pihak lainnya dianggap sedang mendapatkan ‘ujian’ untuk meningkatkan kadar keimanannya. Perbedaan pemaknaan atas pandemi ini merupakan salah satu hal yang jamak kita temui di sosial media.
Keadaan diperburuk dengan sikap saling lempar kesalahan. Pemerintah menyalahkan para masyarakat yang ‘bandel’ dalam merespon berbagai himbauan dan anjuran pemerintah. Di sisi lain, tidak sedikit masyarakat yang menyalahkan pemerintah yang dianggap lamban dalam merespon virus ini. Seluruh keputusan yang diambil oleh pemerintah dianggap tidak tepat dan hanya memperburuk keadaan.
Menyedihkan, namun inilah yang terjadi. Dalam merespon sebuah bencana, seringkali kita terjebak pada posisi ‘menghakimi’. Sebelum memahami apa yang sebenarnya tengah terjadi, kita serta merta mengambil alih menjadi ‘hakim’ yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Bahkan, untuk hal yang bersifat abstrak dan metafisik, seperti apakah sebuah bencana bernilai ‘azab’ atau ‘ujian’, kita seringkali langsung menyimpulkan dan menjudge suatu bencana yang menimpa seseorang dengan salah satu dari dua posisi tersebut.
Padahal sejatinya, seseorang yang beriman pada Allah tahu benar bahwa pengetahuan yang dimilikinya tidak sebanding dengan yang Ia miliki. Berbagai ketetapanNya juga seringkali tidak dapat dipahami dengan mudah dengan akal manusia yang serba terbatas. Namun, dalam hal melihat suatu bencana atau kesulitan yang menimpa seseorang, kita dapat melupakan semua keyakinan akan kekuatan Allah. Bahkan, tanpa sadar seringkali kita bertindak seolah-olah bahwa kitalah yang berhak menentukan seseorang untuk mendapatkan hukuman, hadiah, pertolongan, siksaan, dan lain sebagainya.
Kita juga seringkali terjebak pada posisi ‘tidak ingin disalahkan’. Masyarakat tidak ingin disalahkan ketika virus ini merebak, Mereka menuding pemerintah untuk mencari kambing hitam. Sebaliknya, pemerintah juga terkadang terkesan mencari kambing hitam atas ketidakmampuan mereka dalam menanggulangi penyebaran virus ini. Bahkan, hingga hari ini, saya masih menemukan percakapan di grup WhatsApp yang menyatakan bahwa ini adalah sebuah senjata biologis yang diciptakan oleh Cina dan mengalami kebocoran hingga ke seluruh dunia. Berita tersebut secara tidak langsung juga menuduh salah satu pihak sebagai pihak yang terdakwa dan bertanggungjawab atas penyebaran virus ini.
Dengan ini semua, kita melupakan hal penting dalam menyikapi pandemi ini. Pertama, tentang sikap kita terhadap para korban. Meminjam istilah Wim Beuken dalam buku ‘Agama Sebagai Sumber Kekerasan’ yaitu memanusiawikan korban bencana. Para pasien yang positif terjangkit virus ini, apapun latar belakang mereka, gender mereka, etnis mereka, status ekonomi, bahkan agama mereka, adalah korban yang memerlukan pertolongan medis dengan segera. Sudahi berbagai klaim dan tuduhan tentang mereka yang pendosa atau tidak. Satu hal yang pasti adalah mereka membutuhkan pertolongan segera, baik pertolongan medis, moril, maupun materiil.
Di samping itu, jangan jadikan para pasien positif, PDP, atau ODP sebagai ‘makhluk asing’ pembawa penyakit. Dari sifat virus ini, tidak seluruh orang dapat merasakan langsung efek ketika virus ini mulai masuk ke dalam tubuhnya. Terlebih, virus ini bisa bertahan dalam waktu lama ketika menempel di benda-benda yang sering terpegang atau di udara di ruang – ruang publik. Mungkin kita terlalu sering menghakimi seseorang yang sakit perut dengan tuduhan ‘kebanyakan makan sambal’ atau ‘telat makan’ daripada segera mengambilkannya obat sakit perut. Inilah yang saat ini juga tengah terjadi.
Beberapa hari ini juga beredar di mana para tenaga medis yang meninggal karena tertular pandemi ini juga tidak sedikit. Bahkan, di salah satu kota, jenazah tenaga medis yang terjangkit virus ini justru ditolak warga dengan alasan mereka tidak ingin tertular penyakit tersebut. Padahal, jenazah tersebut adalah tenaga medis yang mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan dan kesembuhan orang lain. We can see many humans there, but not humanity.
Kedua, berhentilah mencari kambing hitam dan menimpakan efek bencana ini kepada sekelompok manusia. Ini bukanlah saat yang tepat untuk semakin meruncingkan perbedaan, memecah belah, dan mengkotak-kotakkan masyarakat. Justru, ini adalah salah satu alasan kuat bagi kita semua untuk mulai berdamai dengan pihak lain dan membangun masyarakat yang tangguh bencana.
Kadangkala, butuh satu pukulan keras bagi seekor kuda untuk dapat melaju dengan kencang. Saat inilah pukulan keras bagi kita semua untuk mulai tersadar dari tidur panjang kita. Selama tertidur, kita tidak sadar bahwa kita telah terkotak-kotakkan dengan isu etnis, ras, suku, negara, ideologi, kepercayaan, hingga pilihan politik. Sekarang adalah saat kita harus membuka mata dan menyadarkan diri kita bahwa persatuan kita merupakan sebuah kunci untuk melewati masa-masa sulit ini.
Ketiga, ini adalah waktunya untuk introspeksi diri dan mulai berbicara dengan diri kita sendiri. Kita acapkali menjadi pribadi yang serius dengan urusan orang lain, namun abai dengan urusan pribadi kita. Kita sering menyepelekan hal-hal kecil yang berkaitan erat dengan kesehatan diri, mulai dari kebersihan diri, kebersihan pakaian, kebersihan tempat tinggal hingga kebiasaan mencuci tangan. Saat ini adalah waktunya kita mulai mendisiplinkan diri kita. Peduli kepada orang lain merupakan hal terpuji. Namun, perlu didahului dengan mempedulikan diri sendiri. Bukankah salah satu instruksi di pesawat adalah memakai masker oksigen dahulu sebelum membantu orang lain menggunakannya?
Berbagai himbauan dan anjuran dari pihak berwenang, mulai dari WHO, Pemerintah, dan Tenaga Medis perlu kita dengarkan dan laksanakan. Ketaatan kita dalam menjaga kebersihan, mencuci tangan, social / physical distancing, hingga tidak keluar dari rumah kecuali bila dalam keadaan terpaksa merupakan salah satu sarana dalam memutus mata rantai penyebaran virus ini. Meskipun tidak terbatas pada hari-hari ini, namun setidaknya kita mulai menyadari bahwa kepedulian kita terhadap diri sendiri dapat menyelamatkan diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Mungkin di lain waktu kita akan lebih dapat menyadari bahwa ketika kita mengendarai motor dengan kecepatan yang normal, hal tersebut merupakan wujud kepedulian kita pada keselamatan diri kita sendiri dan keselamatan orang-orang di sekitar kita.
Akhirnya, semoga dengan bencana kemanusiaan ini, kita mampu memetik berbagai hikmah yang ada. Sekali lagi, dengan mengedepankan teologi yang humanis, kita dapat lebih menolong banyak nyawa daripada menghabiskan waktu dan tenaga dalam berdebat untuk menentukan apakah ini ‘azab’ atau ‘ujian’ atau mencari kambing hitam dari kejadian ini. Inilah waktunya kita berjalan berdampingan, menguatkan diri kita, saling menguatkan sesama umat manusia untuk melewati hari-hari sulit ini. Salah satu kata pepatah Arab berbunyi:
Tak ada kesedihan yang kekal, tak ada (pula) kebahagiaan yang abadi
Tak ada kesengsaraan yang bertahan selamanya, pun demikian halnya dengan kemakmuran
*) Artikel ini terbit di dalam kumpulan Esai “Covid 19: Wabah, Fitnah, dan Hikmah”
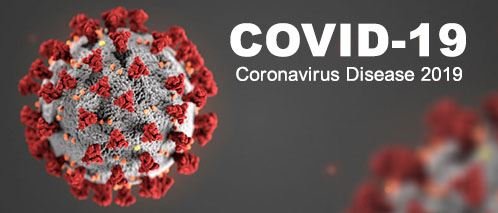


Pingback: Buku Bincang Islam di Era Covid-19 (2022) - Yuanggakurnia.com